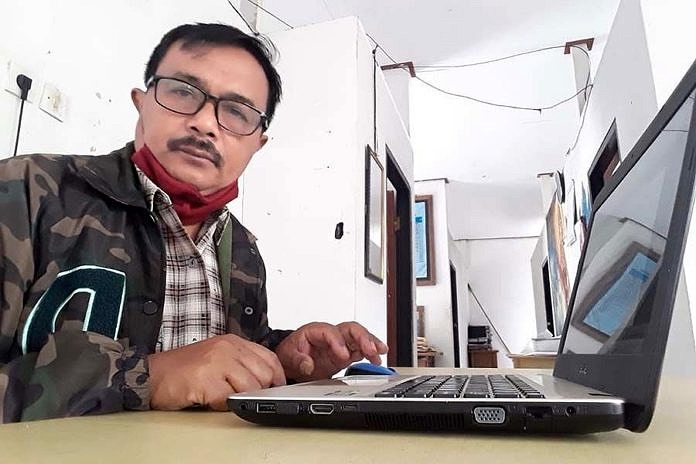
Oleh A.A. Ketut Jelantik
Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat menggagas program membaca Satu Buku Satu Minggu (Sabusami). Gagasan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia yang masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukan Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 81 negara yang berpartisipasi dalam tes yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ini.
Dalam aspek membaca, skor literasi siswa Indonesia hanya mencapai 359 poin, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 476 poin. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar siswa di Indonesia kesulitan memahami, menganalisis, dan merefleksikan isi bacaan yang relatif sederhana.
Rendahnya kemampuan literasi tersebut sekaligus menjadi indikator kemampuan siswa di Indonesia untuk berpikir kritis, bernalar dan keterampilan memecahkan masalah masih kalah jauh dibandingkan dengan siswa dari negara lain. Dalam kontek ini maka gagasan Wamendikdasmen tersebut merupakan sebuah keniscayaan dan patut diapresiasi.
Sedikitnya ada tiga permasalahan yang akan menjadi tantangan implementasi program Satu Buku Satu Minggu (Sabusami) ini yakni keterbatasan jumlah buku yang berkualitas, kompetensi guru, serta peran para orang tua. Tulisan ini mencoba untuk mengurai tiga permasalahan tersebut. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam laporannya tahun 2023 menyebutkan hanya sekitar 28% sekolah yang memiliki perpustakaan dengan koleksi yang memadai. Lebih dari 70 % sekolah di Indonesia bermasalah dengan penyediaan buku-buku berkualitas baik dari segi jenis maupun kontennya.
Terbatasnya jumlah buku berkualitas tersebut tentunya sangat berdampak terhadap minat baca siswa. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan Early Grade Reading Assessment (EGRA) tahun 2014 lalu.
Studi ini menyebutkan di 8 provinsi di Indonesia sekitar 50% siswa kelas awal SD tidak memahami isi teks sederhana yang mereka baca bahkan banyak diantara mereka yang belum mengenal huruf. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Covid-19 ikut andil dan menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan literasi baca di Indonesia.
Meski demikian, dukungan ekosistem literasi, baik di sekolah maupun di rumah juga ikut andil atas rendahnya minat baca di Indonesia. Buku belum menjadi kebutuhan pokok. Kegiatan membaca belum menjadi kebiasaan, Perpustakaan sekolah lebih sering menjadi ruangan penyimpanan ketimbang pusat belajar aktif.
Ironisnya, budaya lisan masih sangat kental di tengah masyarakat. Dominasi media visual seperti gawai serta konten digital singkat turut memperburuk kemampuan membaca mendalam (Comprehenship Reading). Anak-anak lebih terbiasa dengan teks singkat, cepat, dan dangkal. Padahal, kemampuan berpikir kritis justru dibangun melalui pembacaan teks panjang dan reflektif.
Ekosistem sekolah yang kurang mendukung juga berkontribusi terhadap rendahnya budaya baca siswa. Dalam kontek ini maka peran guru sebagai salah satu komponen ekosistem sekolah menjadi sangat urgen. Sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru, guru akan menjadi referensi hidup bagi para siswanya di sekolah.
Apa pun yang dilakukan guru akan selalu dijadikan rujukan oleh siswa termasuk kebiasaan membaca. Nah, permasalahan muncul ketika sebagian besar guru kita masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai sosok panutan.
Sangat jamak diketahui jika guru-guru kita ketika waktu istirahat lebih memilih ngobrol di ruang guru, berselancar di dunia maya dan bercengkerama dengan media sosial ketimbang membaca buku di perpustakaan sekolah. Iklim sekolah seperti ini tentu tidak memberikan atmosper positif dalam upaya meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah.
Situasi makin parah ketika selama proses pembelajaran di kelas sebagian besar guru-guru belum mampu mengintegrasikan kebiasaan membaca dalam seluruh siklus pembelajaran. Peningkatan kemampuan literasi melalui budaya baca di kelas masih dilakukan secara parsial. Stigma kemampuan membaca adalah tanggungjawab guru bahasa masih sulit dihilangkan.
Akibatnya fokus proses pembelajaran hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara kaku. Hasilnya lebih banyak dalam bentuk capaian aspek kognitif melalui deretan angka kuantitatif.
Keluarga merupakan herbarium bagi bertumbuhnya budaya baca. Oleh sebab itu peran orang tua menjadi sangat krusial. Orang tua tidak cukup hanya menjadi role model budaya baca, namun pada saat yang bersamaan mereka harus mampu menjadi motivator bagi bertumbuhnya budaya baca.
Kebiasaan membaca buku, koran atau sejenisnya yang rutin dilakukan orang tua pada setiap kesempatan, merupakan praktik baik yang akan berdampak positif bagi anggota keluarga lainnya, khususnya anak-anak.
Pada sisi lain perpustakaan mini dalam keluarga bisa menjadi salah satu motivasi untuk membangun mudaya baca dalam keluarga. Perpustakaan mini tersebut harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang sangat menarik dan sekaligus menjadi spot berkumpul bagi seluruh anggota keluarga.
Menjadikan buku sebagai bentuk hadiah dalam perayaan ulang tahun, atau perayaan keberhasil juga bisa menjadi langkah lain untuk membangun budaya baca dalam keluarga. Tentu masih banyak terobosan lain yang bisa dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun yang paling penting hendaknya dilakukan secara konsisten.
Program membaca satu buku satu minggu (Sabusami) yang digagas Wamendikdasmen merupakan investasi sederhana namun akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masa depan Indonesia. Bangsa yang besar dan literat akan mampu menguasai dunia. Sebaliknya, bangsa yang gagal adalah bangsa yang mengabaikan budaya membaca.
Sebagaimana yang diungkapkan Ray Bradbury, seorang sastrawan Amerika. “Kalau kamu ingin menghancurkan suatu bangsa hancurkan dulu kemampuan membacanya,” Mari kita ubah budaya diam menjadi budaya baca, budaya menonton menjadi budaya memahami dan budaya tugas menjadi budaya pembelajar.
Penulis, Pengawas Sekolah Dikpora Bangli












