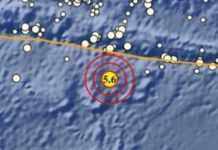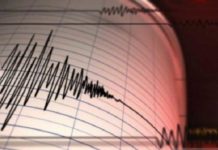Oleh Agung Kresna
Likuifaksi berpotensi terjadi di Bali Selatan. Demikian headline Bali Post (17/10) yang menyiratkan adanya potensi bencana alam ikutan akibat gempa bumi di Pulau Dewata. Informasi tersebut –jika akurasinya tinggi, tentu akan membuat masyarakat Bali mengernyitkan dahi. Mengingat bahwa kewaspadaan atas daerah rawan gempa bukan masalah gempa akan terjadi atau tidak, namun lebih pada kapan gempa akan terjadi sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci menghindari terjadinya bencana yang lebih buruk.
Tentu masih terekam dalam benak kita, bagaimana Perumnas Balaroa di Kecamatan Palu Barat dan kawasan perumahan Petobo “lenyap” akibat peristiwa likuifaksi (liquefaction) sebagai dampak gempa Donggala – Palu yang bermagnitudo 7,4. Sebuah harga sangat mahal yang harus dibayar, akibat ketidaksiapan kita dalam menyikapi kenyataan bahwa warga bangsa ini bermukim di negeri rawan bencana.
Bertemunya tiga lempeng tektonik dunia, telah menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap gempa bumi. Ketiga lempeng tektonik bergerak dalam arahnya masing-masing dan saling bertumbukan di wilayah Indonesia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menyusup ke dalam Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan. Sementara Lempeng Pasifik bergerak dari arah timur ke Indonesia.
Sementara bahaya bencana erupsi gunung berapi datang dari kenyataan bahwa jalur gunung api paling aktif di dunia Pacific Ring of Fire (cincin api Pasifik) terbentang sepanjang 40.000 km dari pantai barat Amerika Selatan mengelilingi Samudera Pasifik, melintasi nusantara dari Aceh hingga tanah Papua menuju New Zealand. Masih ditimpali dengan jalur gunung api aktif nomor dua di dunia Alpide Belt (sabuk Alpide) yang membelit dari Timor melintas ke arah Jawa, Sumatera, menuju Himalaya hingga ke Samudera Atlantik.
Bali Ramah Bencana
Kawasan permukiman di suatu wilayah sudah selayaknya merupakan area yang nyaman dan aman untuk bertempat tinggal bagi para penghuninya. Apalagi jika lingkungan permukiman tersebut merupakan suatu kawasan yang direncanakan, bukan kawasan yang tumbuh alami akibat aglomerasi perkotaan. Sehingga berbagai faktor kenyamanan (convenience) dan keselamatan (safety) harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi suatu kawasan permukiman.
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai perangkat menata suatu provinsi harus benar-benar dijadikan pedoman dan panduan sebelum pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan buatan. Utamanya untuk kawasan publik yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat dalam jumlah besar. Melalui RTRWP semua kawasan publik dapat disiapkan dan direncanakan dengan baik sesuai kaidah tata ruang dan peruntukannya. Sehingga pada kelanjutannya, para pengguna kawasan akan terjaga keselamatan dan kenyamanannya dalam melakukan kegiatan kehidupan kesehariannya.
Data publikasi LIPI pada 2017 tentang kerawanan Bali terhadap gempa, mencatat adanya jalur back-arch (busur belakang) yang terbentang dari utara Flores menerus hingga utara Bali, dan masuk ke daratan di Jawa Timur menjadi Sesar Kendeng yang membentang dari Surabaya, Semarang, hingga Cirebon. Sementara data penelitian lain menunjukkan adanya wilayah rawan likuifaksi di area Bali Selatan, yang banyak berfungsi sebagai area akomodasi pariwisata.
Sedang subduksi aktif lempeng Indo-Australia yang menghunjam lempeng Eurasia, berada hanya sekitar 100 kilometer di selatan Bali. Realitas kondisi rawan bencana ini harus menjadi catatan dalam merencanakan Bali yang ramah terhadap bencana alam.
Pertama, perlu dilakukan peninjauan kembali atas berbagai Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah yang sudah ada selama ini. Apakah Rencana Tata Ruang Kota tersebut sudah mengantisipasi keberadaan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana berat harus menjadi area yang tidak boleh dihuni. Sementara kawasan dengan kerawanan bencana sedang masih mungkin menjadi area terbangun, dengan zonasi kawasan dan building codes yang ketat.
Kedua, harus ada komitmen kuat dalam menegakkan peraturan dan perizinan yang terkait tata ruang dan tata bangunan. RTRW itu sendiri harus dibuat turunannya berupa Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten (RTRK) hingga Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kabupaten (RDTRK). Berlanjut dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai panduan dalam penyusunan aturan yang bersifat teknis tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Komitmen ini diperlukan untuk menangkal jatuhnya korban yang sia-sia dalam suatu bencana akibat tidak diterapkannya aturan tata ruang dan tata bangunan dengan benar.
Pada akhirnya, optimalisasi teknologi harus dilakukan pada era serba-digital ini. Kemajuan teknologi konstruksi harus dioptimalkan seiring perkembangan teknologi bahan bangunan, guna menjawab tantangan kerawanan bencana yang ada. Nenek moyang kita telah berhasil melahirkan local genius pada eranya, sehingga generasi masa kini juga harus dapat menciptakan local genius pada era digital.
Sementara mitigasi bencana harus dioptimalkan bagi masyarakat Bali dengan notifikasi melalui perangkat gadget yang sudah menjadi perangkat umum di masyarakat. Masyarakat harus menjadi warga yang sadar bencana, mengingat kita semua bermukim di negeri rawan bencana. Tidak ada salahnya jika kita mengingat wejangan para leluhur: “Jika kita tidak pandai menari, jangan salahkan lantai yang berjungkit”.
Penulis, arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar